
 |
| Mengusut Jejak Pencucian Uang: Saat Hukum Anti Money Laundering Diuji Integritasnya (Foto: Spesial) |
Penulis: Fauziah
Tindak pidana pencucian uang (TPPU) masih menjadi ancaman serius bagi sistem keuangan nasional. Di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks, praktik memindahkan, menyamarkan, dan mengaburkan asal-usul dana hasil kejahatan kini semakin sulit dilacak.
Di sinilah hukum anti money laundering berperan sebagai benteng utama dalam menjaga integritas sistem keuangan dan penegakan hukum. Pengaturan hukum mengenai TPPU di Indonesia berakar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-undang ini menggantikan regulasi sebelumnya dan memperluas cakupan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencucian uang. Melalui regulasi tersebut, negara menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti setiap hasil tindak pidana yang dialihkan ke sistem keuangan formal.
Tujuan utamanya bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi juga memutus rantai ekonomi hasil kejahatan agar tidak kembali berputar dalam sistem yang sah.
Dari perspektif normatif hukum, pengaturan anti money laundering dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam sistem keuangan.
Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh lembaga keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini berfungsi sebagai "intelijen keuangan" negara, yang memiliki peran penting dalam mendeteksi dan menelusuri aliran dana mencurigakan sebelum menjadi bukti pidana.
Dalam praktiknya, tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri. Ia selalu berkaitan dengan tindak pidana asal (predicate crime) seperti korupsi, narkotika, penipuan, atau kejahatan perpajakan.
Oleh sebab itu, efektivitas hukum anti money laundering bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menelusuri keterkaitan antara tindak pidana asal dengan proses penyamaran uang. Dalam banyak kasus, pelaku berusaha menumpuk dan memutar dana haram melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit, termasuk melalui perusahaan cangkang, aset properti, hingga investasi digital.
Korelasi antara pengaturan hukum dan tingkat terjadinya tindak pidana pencucian uang menunjukkan bahwa semakin kuat instrumen hukum yang diterapkan, semakin besar peluang terungkapnya kejahatan keuangan. Namun, di sisi lain, kompleksitas sistem keuangan modern juga menuntut hukum untuk terus beradaptasi.
Munculnya fintech, aset kripto, dan transaksi lintas negara menghadirkan tantangan baru yang menuntut pembaruan regulasi agar mampu menjangkau modus-modus kejahatan yang lebih canggih. Pemerintah telah memperkuat langkah melalui kerja sama internasional dan penyesuaian dengan standar Financial Action Task Force (FATF), lembaga global yang mengatur kebijakan anti pencucian uang di tingkat dunia.
Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga integritas penegak hukum. Dalam sejumlah perkara, muncul indikasi bahwa penegakan hukum terhadap kasus TPPU masih belum maksimal, baik karena keterbatasan kemampuan investigasi maupun lemahnya koordinasi antar lembaga.
Padahal, keberhasilan hukum anti money laundering sangat ditentukan oleh kemauan politik (political will) dan konsistensi aparat dalam menjalankan mandat undang-undang. Dalam konteks penegakan hukum, PPATK bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan penting dalam mengintegrasikan sistem informasi keuangan dan penyidikan pidana.
Kolaborasi antar lembaga ini mempercepat proses pelacakan aset hasil kejahatan serta memperkuat posisi Indonesia di mata internasional. Pengakuan terhadap kemajuan sistem hukum anti money laundering nasional juga terlihat dari keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh FATF, yang menandai peningkatan kepercayaan global terhadap sistem hukum keuangan kita.
Namun, penting disadari bahwa keberadaan hukum bukan sekadar instrumen represif untuk menghukum pelaku. Ia juga merupakan mekanisme pencegahan yang menuntut keterlibatan masyarakat dan dunia usaha. Lembaga keuangan wajib menerapkan Know Your Customer Principle (KYC) untuk mencegah penyalahgunaan sistem perbankan oleh pihak yang ingin menyembunyikan dana haram. Dalam konteks ini, pendidikan hukum dan kesadaran publik menjadi faktor yang tak kalah penting dari aspek penindakan.
Ke depan, tantangan utama hukum anti money laundering adalah memperkuat koordinasi antar lembaga dan memperluas cakupan pengawasan terhadap instrumen keuangan digital. Reformasi regulasi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama di kalangan aparat penegak hukum dan penyidik keuangan. Dengan demikian, hukum dapat menjalankan perannya secara utuh: melindungi sistem keuangan nasional, memastikan keadilan, dan menegakkan integritas negara dari ancaman uang kotor.
[Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara (USU)]


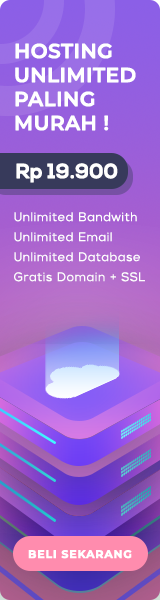



%20Sonia%20Devi%20Lawolo.jpeg)



